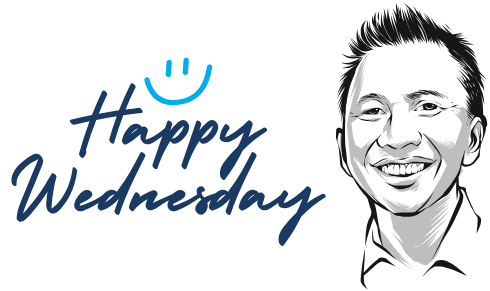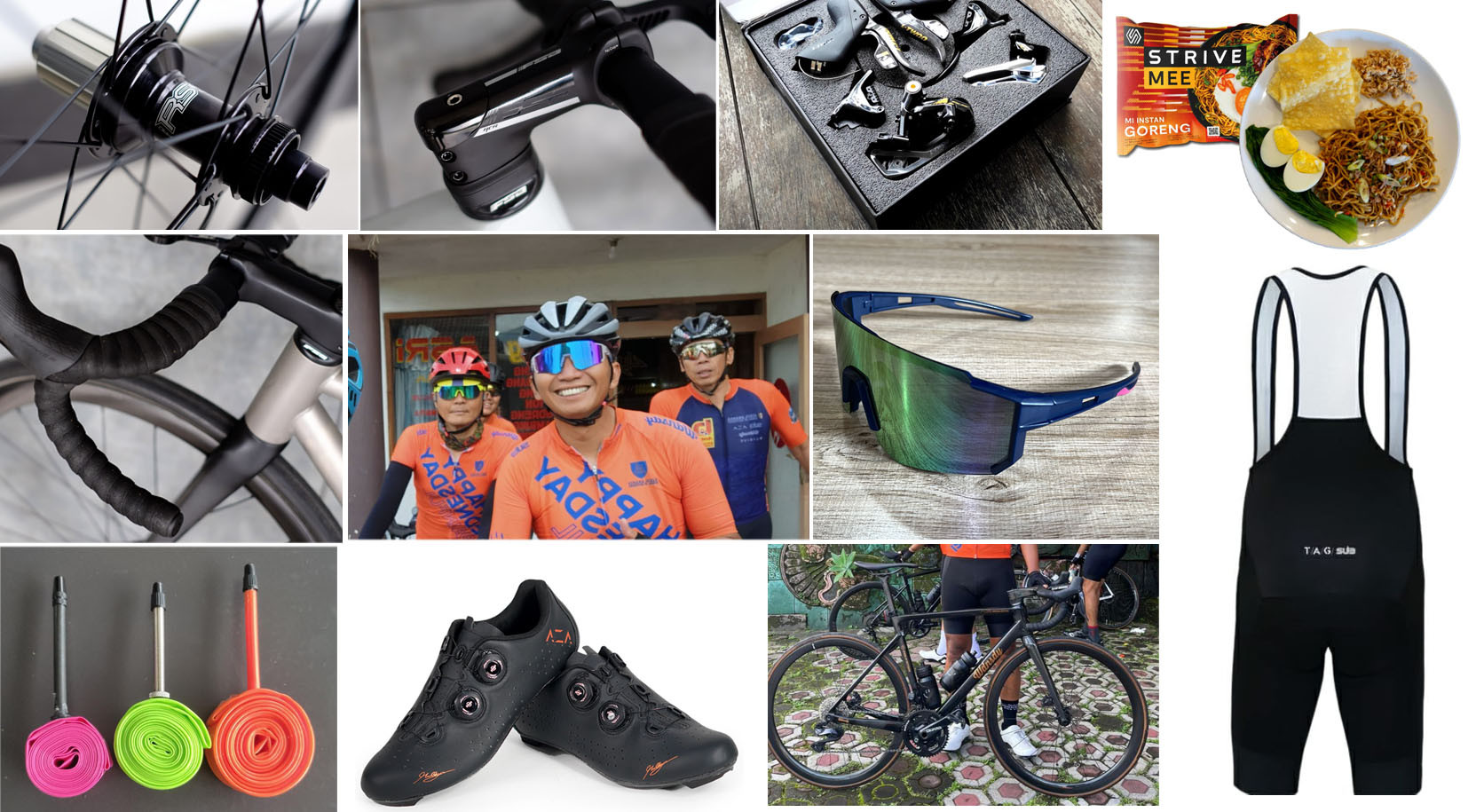Membuat keputusan. Alangkah mengerikannya. Apalagi kalau menyangkut nasib orang banyak. Apalagi kalau tidak banyak orang memahaminya. Apalagi kalau banyak orang bakal tidak setuju. Alangkah berisikonya.
Saya telah beberapa kali membuat keputusan-keputusan “mengerikan” itu. Keputusan-keputusan berisiko. Keputusan-keputusan yang tidak populer.
Mungkin saya termasuk mengambil risiko lebih banyak dari kebanyakan orang. Walau mungkin masih ada banyak orang yang membuat lebih banyak lagi keputusan-keputusan lebih menyeramkan.
Tentu saja, tidak semua keputusan itu keputusan yang berhasil. Kadang memang salah. Kadang sebenarnya baik tapi tidak terlihat demikian. Tujuannya baik, dan sebenarnya memang benar-benar untuk kebaikan, tapi dalam eksekusi dan follow up-nya tidak sesuai rencana. Sehingga kesannya bukan keputusan yang baik.
Tapi, sejak dulu, ada satu hal yang selalu ingat setiap kali akan membuat keputusan besar: Bahwa mayoritas belum tentu benar.
Saya percaya bahwa minoritas justru bisa jadi yang baik dan benar. Hanya waktu yang akan menunjukkan dan membuktikan.
Mark Twain, penulis kondang Amerika Serikat, pernah bilang: “Setiap kali kita berada di posisi mayoritas, justru itulah waktu bagi kita untuk berhenti dan merenung.”
Dan, tentu saja, saya banyak belajar dari ayah saya. Seorang risk taker. Seseorang yang berani mengambil keputusan dan menanggung risikonya. Bagi dia, keputusan baik harus berani diambil walau belum tentu populer. Bahwa tujuan keputusan itu adalah membuat orang banyak lebih baik, bukan untuk membuat orang banyak lebih senang.
Percuma membuat orang senang, kalau pada akhirnya menjerumuskan ke situasi yang lebih buruk. Lebih baik mengambil risiko dan membuat orang tidak senang, tapi pada akhirnya akan lebih baik untuk semua.
Saya menyadari betul, tidak mudah untuk menjadi orang seperti ini. Tidak banyak yang berani menjadi seperti ini. Bahkan mungkin mayoritas tidak berani.
Saya pun belum sehebat atau seberani dia dalam mengambil keputusan-keputusan itu.
Tapi ada beberapa keputusan besar yang akan selalu saya kenang. Salah satunya pada 2010. Saat saya kali pertama terang-terangan memberikan dukungan dalam pemilihan Wali Kota Surabaya.
Waktu itu, Bu Risma belum terlalu kondang. Tidak banyak yang menyangka dia bisa maju dan terpilih sebagai wali kota. Kandidat unggulan waktu itu adalah Mas Arif Afandi, seseorang yang saya sangat kenal dengan sangat baik.
Mas Arif waktu itu wakil wali kota, sekaligus senior saya sebagai pemimpin redaksi di Jawa Pos. Begitu dia menjadi wakil wali kota, sayalah yang menggantikannya sebagai pemimpin redaksi pada 2005.
Sebenarnya, andai waktu itu Mas Arif jadi wali kota, saya yakin Surabaya akan sangat baik-baik saja. Dia orang pekerja, sudah terbiasa di lingkungan yang terus kerja, kerja, dan kerja.
Bisa dibilang, waktu itu Mas Arif adalah pilihan emas.
Namun, dengan segala hormat kepada Mas Arif (hubungan kami sekarang tetap sangat baik), waktu itu saya merasa Bu Risma seperti berlian. Seorang “penjaga kota” yang luar biasa. Cocok untuk Surabaya, yang telah menjalani masa “recovery” luar biasa di bawah Mas Bambang DH. Setelah keruwetan besar di era sebelumnya.
Saya selalu bilang ke orang, bahwa waktu itu Surabaya beruntung. Bisa memilih emas atau berlian. Tidak semua kota bisa beruntung seperti itu. Bahkan sebuah negara pun belum tentu beruntung, mendapatkan dua pilihan pemimpin yang kaliber emas.
Ibaratnya, kadang kota, provinsi, atau negara berhadapan dengan pilihan sulit: Mau kucing dalam karung, atau kucing yang sudah ketahuan kulitnya. Yang satu ada elemen gambling-nya, yang satu lagi seperti berserah pasrah walau mungkin tidak spektakuler.
Ketika memutuskan mendukung Bu Risma, minta ampun hebohnya. Baik di sekeliling saya dan di luaran. Rasanya banyak pihak siap menerkam saya kapan saja, menghancurkan dengan segala cara. Apalagi waktu itu, secara survei (“suara mayoritas”) menyatakan Bu Risma bukan unggulan.
Tapi saya berani mengambil risiko itu. Tohdalam hati saya sadar seribu persen, bahwa niatan saya demi kebaikan.
Alhamdulillah, Bu Risma tidak mengecewakan Surabaya. Setiap kota selalu ada tantangannya, tapi Surabaya termasuk yang paling nyaman ditinggali di Indonesia (dan saya sering keliling!).
Jadi saya tidak harus merasakan cognitive dissonance, menyesali keputusan saya dulu.
Saat tulisan ini dibuat, tentu saya sadar betul bahwa tulisan Happy Wednesday 11 ini muncul bertepatan dengan hari memilih nasional. Hari ini, 17 April 2019, warga Indonesia harus membuat keputusan. Apa pun keputusannya, itu merupakan keputusan yang berani dan sama-sama ada risikonya. Mungkin tidak langsung, tapi dalam lima tahun ke depan.
Saya ingin mengutip lagi, kali ini dari Albert Einstein. Sang jenius bilang, “Yang benar tidak selalu populer dan yang populer tidak selalu benar.”
Inilah ngeri-ngeri sedapnya memilih seperti ini. Mayoritas (yang menang) pada akhirnya bisa salah. Yang senang (awalnya) belum tentu baik di kemudian hari…