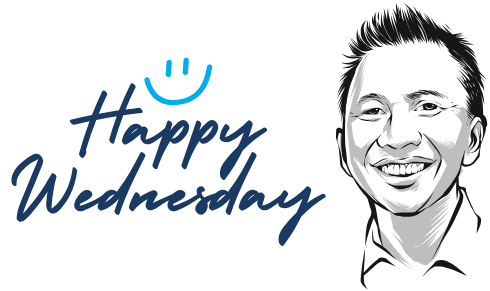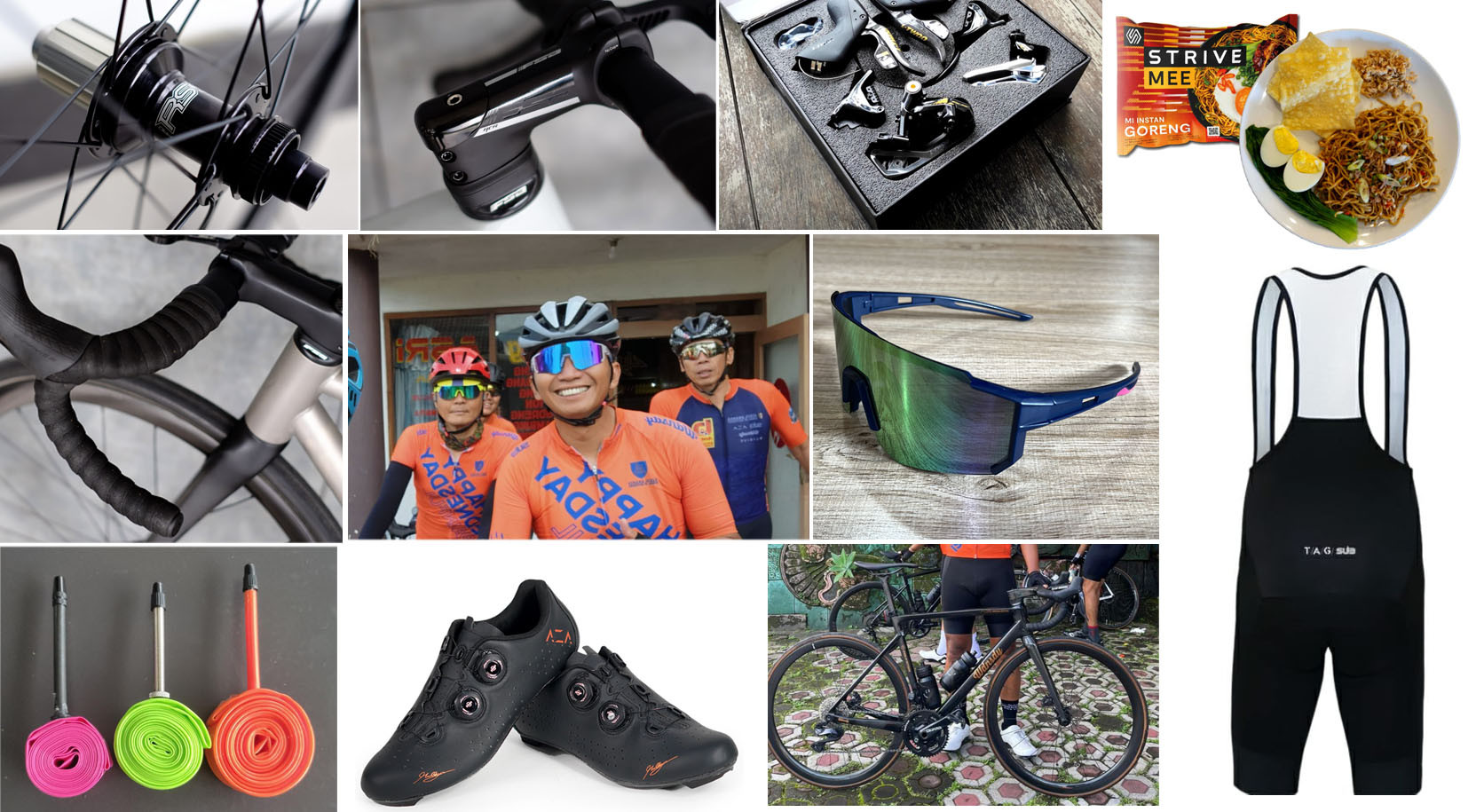Sudah lebih dari 25 tahun ini, bulan Maret membuat saya berdebar-debar dan berbahagia. Karena bulan inilah sesuatu yang sangat saya cintai kembali bergulir: Balap Formula 1.
Sejak SMP saya sudah menggandrungi ajang ini. Karir media dan menulis saya juga terbantu oleh ajang ini. Cita-cita jadi komentator televisi pun sudah tercapai selama bertahun-tahun. Bahkan lebih dari sepuluh tahun, di beberapa stasiun televisi yang berbeda!
Sekarang saya memang sudah “pensiun” jadi pengamat/penulis F1. Ketika bepergian di berbagai kota, masih saja ada orang yang mengenal saya sebagai komentator F1, dan bertanya kapan saya akan kembali tampil.
Sebagai penegasan: Saya tidak akan kembali. Sudah cukup.
Meski demikian, bukan berarti saya tidak lagi cinta F1. Bukan berarti saya tidak lagi mengikuti F1. Sampai hari ini, SETIAP HARI, saya masih mengikuti perkembangan F1. Sesekali saya juga masih bertemu teman-teman penggemar F1.
Apalagi komunitas F1 Mania Surabaya termasuk kompak dan konsisten bikin pertemuan dan kegiatan. Termasuk janjian pergi nonton bareng ke luar negeri.
Dulu, saya pernah membaca kalau balap mobil (khususnya F1) itu olahraga atau tontonan yang sulit untuk disukai bagi pemula. Terlalu banyak detailnya, terlalu banyak aspek teknisnya. Tapi begitu suka, biasanya dia akan cinta selamanya. Karena F1 selalu menawarkan sesuatu yang baru. Penggemarnya harus terus mengikuti dan belajar tanpa henti!
Saya merasa bahwa saya pribadi adalah bukti konkretnya.
Jadi, saya akan menggunakan tulisan ini sebagai closure saya pada dunia F1. Kesempatan untuk bercerita, bagaimana saya dulu mulai suka, bagaimana puluhan tahun menyukai, dan kira-kira kelak bagaimana.
Tulisan ini sekaligus untuk “temu-kangen” dengan penggemar-penggemar F1 di Indonesia. Khususnya yang selama ini mengikuti komentar saya di televisi, juga tulisan saya di koran dan majalah.
***
Kebetulan, saya menulis ini di ruang hobi saya (my fortress of solitude). Di sekeliling saya banyak sepeda dan sepatu yang saya koleksi. Plus, di sekeliling saya ada ribuan miniatur mobil F1, yang sudah saya koleksi sejak masih SMP dulu.
Percaya atau tidak, saya mulai cinta F1 gara-gara merakit model miniaturnya. Waktu SMP, saya (seperti banyak anak lain) hobi main Tamiya 4WD. Merakit, memodifikasi, dan balapan di mal-mal.
Sebagai variasi, saya lantas membeli model kit Tamiya yang F1. Harus mengecat, mengelem, dan merakit sendiri model plastik skala 1/20.
Anda yang koleksi model kit Tamiya pasti tahu, kalau di setiap boksnya ada buku panduan merakit. Di bagian depannya selalu ada gambar dan tulisan deskripsi dengan mobil yang akan kita rakit.
Dari situlah saya “belajar” tentang mobil F1. Kenapa mesinnya di belakang kokpit. Kenapa sayapnya seperti itu. Kenapa bentuknya seperti itu. Kenapa lain-lainnya seperti itu.
Makin lama, makin penasaran. Cari buku, kliping Tabloid Bola tulisan Mas Arief Kurniawan, dan bahan-bahan lain. Semua yang tentang F1 saya lahap. Belum ada internet.
Ketika SMA ke Amerika, kesempatan belajar makin besar. Walau negara itu tidak gila F1, tapi toko bukunya lengkap. Majalah-majalahnya lengkap. Koleksi miniatur F1 juga semakin gampang.
Pengin nonton langsung, di usia 18 tahun (1997) saya urus visa sendiri. Terbang sendiri ke Montreal, Kanada, nonton langsung di Sirkuit Gilles Villeneuve. Seperti anak gila, pakai baju Benetton-Renault dan mendukung Jean Alesi, pembalap favorit saya waktu itu (anak kedua saya sekarang bernama Alesi).
Bisnis koran keluarga membantu saya punya outlet menulis. Terus mengirimkan tulisan-tulisan tentang F1, yang di Indonesia masih sangat jarang.
Saat wisuda kuliah pun, saya masih sangat F1. Topi wisuda saya seharusnya warna hitam polos. Namun saya modifikasi. Saya bikin bagian kotak itu berwarna kuning, dengan garis tebal biru gelap dan hijau. Seperti warna helm Ayrton Senna, pembalap idola saya sepanjang masa (anak pertama saya bernama Ayrton).
Lucu seharusnya kalau dilihat dari belakang. Di saat semua topi berwarna hitam, ada satu yang kuning mencolok!
***
Pulang ke Indonesia awal 2000, tiba-tiba ada orang mengajak saya siaran radio soal F1. Namanya Mas Dewo Pratomo, yang sampai sekarang masih jadi sahabat/motivator/penghibur. Saya serius, dia kocak. Dia pula yang mendorong dan mengupayakan supaya saya bisa makin “tampil” di dunia F1 Indonesia.
Kemudian, muncul kesempatan jadi komentator F1 di RCTI. Hanya sekali di stasiun itu. Mungkin karena saya masih dianggap terlalu muda, sedangkan di sana ada banyak yang lebih senior.
Tidak apa-apa. Waktu saya segera tiba. Saya berlanjut jadi komentator “lebih tetap” saat F1 pindah ke TPI. Mereka beralasan mencari yang masih “muda dan segar.” Lalu lanjut lagi ke Global TV. Di sela-sela, saya juga sempat jadi komentator NASCAR di Indosiar, dan berkali-kali menolak jadi komentator MotoGP karena ingin fokus.
Dalam perjalanannya, ada majalah F1 Racing waktu itu meminta saya menulis kolom secara rutin. Ini adalah sebuah kebanggaan, menulis untuk media yang bukan berkaitan dengan keluarga!
Banyak acara nonton bareng juga mengundang saya. Entah itu di Jawa Tengah, atau di Bali.
Kadang, menengok ke belakang, hidup saya ini aneh juga. Walau hidup utama saya bukan dari F1, tapi saya punya “karir F1” yang lumayan panjang dan lengkap.
Sampai hari ini, salah satu pengalaman paling membanggakan adalah bisa tampil di televisi bersama Mas Arief Kurniawan. Orang yang tulisannya saya kliping saat masih SMP dulu!
***
Formula 1 sekarang memang tidak lagi seperti dulu. Saya termasuk yang menikmatinya saat masih “old school.” Saat mobil-mobil F1 terlihat begitu eksotis. Saat para pembalapnya mempertaruhkan nyawa bak gladiator. Saat segalanya masih “kampungan” tidak terpoles.
Baru-baru ini, saya berdiskusi dengan Wawan “Dalbo,” seorang pengusaha properti di Jakarta yang juga doyan F1 (dan sepeda). Kita ngobrol soal mobil favorit kita. Ternyata, kesukaan kita sama: Tyrrell P34 yang memiliki enam roda.
Mobil itu keluar era 1976-1977, saat saya baru akan dibuat dan kemudian lahir!
Mobil favorit saya yang lain: Jordan 191, dengan warna hijau 7up-nya yang cantik anggun. Juga Leyton House CG901, dengan warna birunya yang memukau. Tidak ketinggalan Lotus 72 yang pipih dengan warna hitam emas mewah.
Dan ini pertanda kalau saya semakin tua. Mobil-mobil F1 sekarang tidak membuat saya “bergetar” sama sekali. Regulasi yang semakin ketat membuat desain semakin seragam. Warna juga tidak banyak yang layak disebut “iconic.”
Apalagi bunyi mesin hybrid sekarang. Benar kata Mas Dewo, mendengar mobil F1 di sirkuit sekarang seperti mendengar “balapan bemo.”
Saya ingat betul pada 1997, berdiri di sisi trek lurus Sirkuit Gilles Villeneuve. Mendengar bunyi mesin-mesin V8 dan V10 yang melengking begitu tinggi, mendengar bunyi perpindahan gir yang menggelegar seperti petir.
Formula 1 sedang berupaya keras supaya faktor mengasyikkan itu bisa kembali. Semoga saja bisa. Kalau tidak, menurut saya hilang sudah salah satu faktor yang membuat mobil-mobil itu begitu “magis.”
***
Saya masih cinta F1. Saya masih mengikuti F1. Saya masih berupaya keras untuk tidak melewatkan satu pun lomba. Mungkin saya akan terus menyukai F1 sampai ending saya nanti.
Di sisi lain, sesuatu yang begitu besar seperti F1 juga terancam untuk tidak eksis selamanya. Sudah bukan rahasia, rating televisinya tidak seperti dulu. Penonton di sirkuitnya tidak seperti dulu. Tim-tim yang dulu berjaya, seperti McLaren dan Williams, sekarang seperti tidak punya taring.
Liberty Media, pemilik F1 sekarang, sedang kerja keras untuk menjaga eksistensi dan kebesarannya. Lebih aktif menyelenggarakan kegiatan untuk fans, lebih membuka akses untuk fans, dan lain sebagainya.
Masalahnya, dunia masa depan jangan-jangan sudah tidak lagi minat dengan F1. Masih adakah mobil di masa depan? Saya tidak lama lalu membaca, di Amerika saja (tempatnya mobil) anak muda sudah tidak lagi punya mimpi besar naik mobil.
Pendidikan cinta lingkungan, perkembangan sistem transportasi masal, disebut membuat mobil tidak lagi seperti dulu.
Sponsor pun tidak seperti dulu. Dan kita semua tahu, hidup tidak cukup pakai cinta. Harus ada fulusnya.
Sebagai penggemar berat/pecinta F1, saya tentu berharap generasi-generasi selanjutnya bisa tetap menikmati ajang ini. Tapi saya realistis. Ada kemungkinan F1 pun tidak akan selamanya. Dalam hidup ini tidak ada yang selamanya bukan?
Mungkin juga tidak apa-apa begitu. Yang terpenting bagi saya dari F1 kan bukan masa depan ajang itu. Yang terpenting, dan hikmah terbesar yang saya dapat dari F1: Ada banyak sahabat yang saya dapatkan selama ini gara-gara sama-sama hobi F1.
Ada yang masih sangat aktif mengikuti F1. Ada yang masih akan janjian nonton bareng ke luar negeri. Walau ada pula yang sudah tiada.
Setelah lebih dari 25 tahun mencintai F1, mungkin saya hanya punya satu penyesalan: Saya tidak pernah foto bareng Michael Schumacher. Saya sudah berkali-kali bertemu, berkali-kali berdekatan, bahkan wawancara. Tapi saya tidak pernah foto sama dia… (*)
PS: Saya bangga pernah hadir langsung di lomba pertama Lewis Hamilton. Saat Fernando Alonso masih “anak ingusan.” Dan yang paling membanggakan: Saat Rio Haryanto menjadi pembalap Indonesia pertama yang ikut balapan F1!