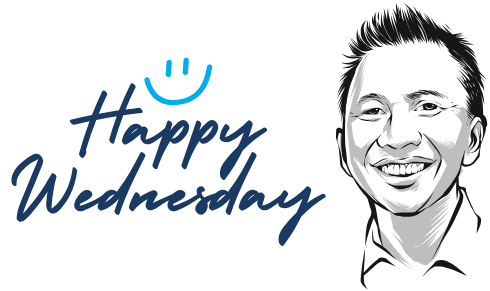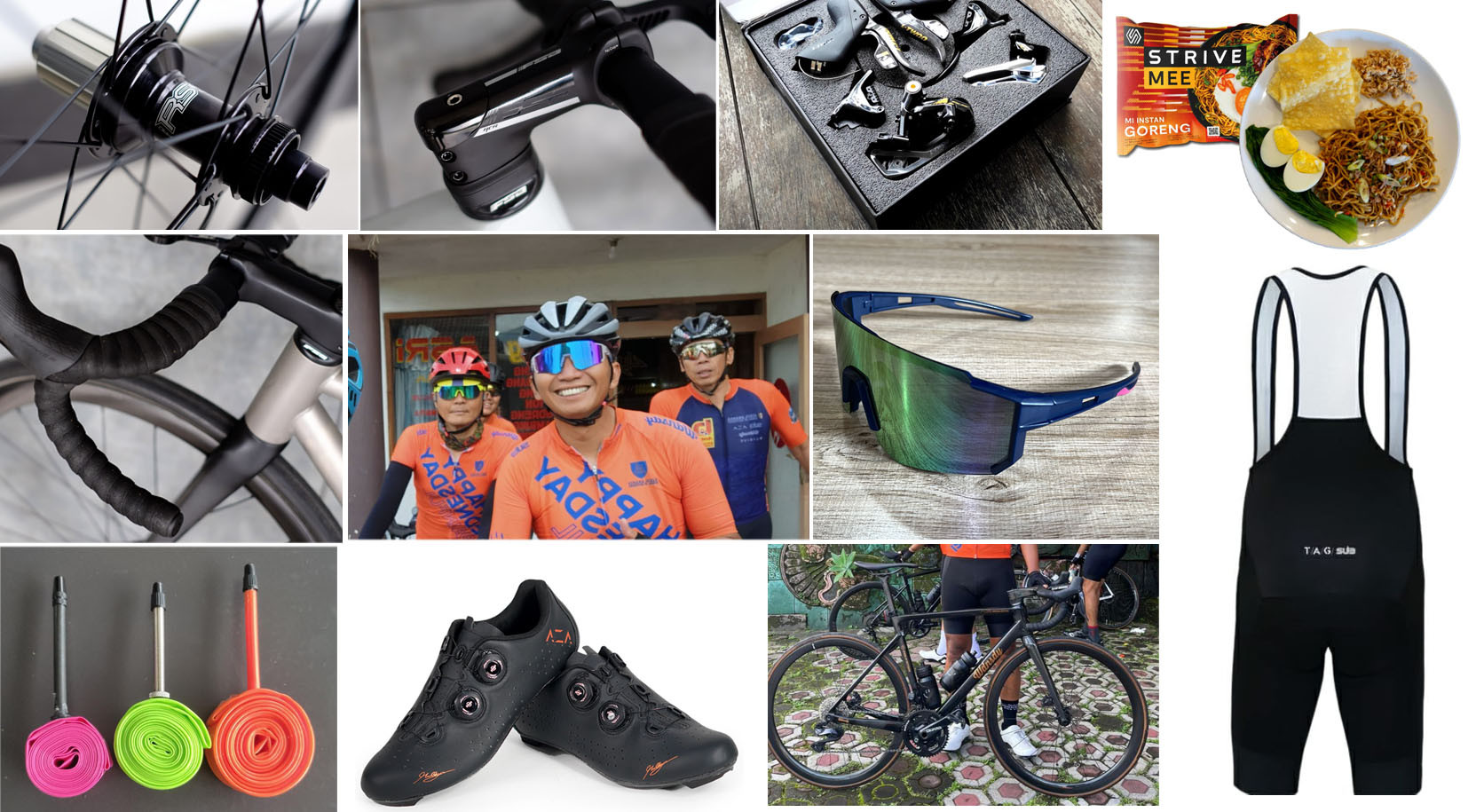Belakangan saya merasa kekurangan asupan. Bukan makanan, melainkan “asupan intelektual.” Gara-gara sudah sangat jarang baca buku, dan semakin hari rasanya semakin sulit bertemu orang yang bisa memberi “pencerahan.”
Bertemu orang banyak, tapi rasanya semakin sulit bertemu orang yang mampu mengedepankan akal sehat. Apalagi, mereka yang mengedepankan akal sehat biasanya memang lebih “tenang,” sangat tidak berisik sehingga seperti tidak kelihatan.
Beberapa bulan lalu, muncul kesempatan untuk mengisi “asupan intelektual.” Kesempatan itu begitu menyenangkan, saya bertekad mengambilnya walau harus terbang ke Singapura.
Ternyata membeli tiket pesawat ke Singapura adalah hal termudah. Tiket untuk mendapatkan “asupan intelektual” itu lebih sulit didapat. Tiketnya sudah habis dalam sekejab.
Istri saya pun memburu tiket itu lewat calo modern. Lewat secondary market. Yaitu perusahaan-perusahaan online yang menyediakan layanan untuk mempertemukan calo dan pembeli.
Wow, harga tiketnya melambung tinggi. Lima kali lipat harga aslinya. Satu tiket setara dengan 200 tiket nonton sepak bola di Surabaya. Kami pun beli tiga tiket. Saya, istri, dan seorang sahabat.
Dalam hati saya berpikir, luar biasa acara ini. Gedungnya bisa menampung 5.000 orang, dan dalam sehari itu akan ada dua sesi. Semua tiket habis terjual. Jadi dalam semalam ada 10.000 orang, dengan harga tiket yang begitu mahal untuk satu orang.
Tapi bagi saya, acara itu tidak boleh dilewatkan. Kepala ini sudah waktunya diberi masukan segar.
Dan malam itu, saya mendapatkannya.
Malam itu, kami benar-benar mendapatkan “sesuatu.”
Bukan sekadar tertawa terpingkal-pingkal, tapi juga mendapatkan “pencerahan.”
Itulah kekuatan stand up comedy yang sebenarnya. Hanya satu orang memegang mic. Panggung polosan. Hanya ada lampu sorot, sebuah bangku kayu tempat menaruh botol air minum.
Orangnya juga tidak dandan aneh-aneh. Hanya pakai kaus biasa, celana jins, dan sepatu kets putih.
Dia hanya perlu berbicara selama satu jam dan 15 menit. Tapi yang level seperti ini, dalam waktu relatif singkat itu dia menghibur kita, menantang akal sehat kita, dan membuat kita jadi lebih kritis terhadap diri kita sendiri dan orang lain. Bukan hanya terhadap lingkungan sekitar, tapi lingkungan secara global.
Malam itu, kami mendapatkan hiburan dan “asupan intelektual” dari seorang Trevor Noah. Komedian asal Afrika Selatan yang sedang melejit namanya di seluruh penjuru dunia, khususnya di Amerika Serikat.
Trevor Noah ini seorang global citizen sejati. Ibunya kulit hitam dari suku Xhosa, ayahnya kulit putih asal Swiss. Karena lahir di zaman apartheid, maka secara resmi Noah adalah seorang anak ilegal.
Trevor Noah lantas meniti karir di dunia entertainment. Menjadi stand up populer, dan kemudian “meledak” di Amerika. Belakangan, pria kelahiran 1984 ini semakin menggila popularitasnya sejak menjadi host acara kondang The Daily Show di Amerika.
Komedi gaya Noah ini termasuk yang paling saya suka. Kombinasi antara lelucon sederhana, observasi sosial (skala global), disertai bumbu guyonan politik. Plus, Noah punya talenta langka. Bisa berbicara lima bahasa, dan bisa menirukan segala jenis aksen secara natural.
Guyonannya sangat mendunia. Dengan mudah bicara soal India, Tiongkok, Eropa, dan tentu saja Afrika dan Amerika.
Silakan cari di YouTube, atau tonton beberapa full show-nya di Netflix. Salah satu yang di Netflix itu tentang liburannya di Bali. Observasinya lucu luar biasa.
Tapi, menonton langsung dengan menonton di layar TV sangatlah beda. Apalagi bisa dapat duduk di barisan depan, lurus depan panggung.
Apa yang dia suguhkan di panggung, tentu sangat beda dengan yang muncul di YouTube atau show-nya di televisi. Ada begitu banyak joke baru dan mendalam yang kami dapatkan malam itu.

Karena di Singapura, tentu dia punya muatan lokal. Menyindir tentang apa yang dia temui selama di negara itu. Dia paling heboh bicara soal makan durian, yang menurut dia adalah buah yang bisa menembus lorong waktu. Karena baunya sama saat baru dibelah dengan saat puluhan tahun kemudian.
Dia juga minta maaf ketika show pertama itu dimulai agak terlambat karena prosesi pemeriksaan keamanan yang ketat. Dia menegaskan, panitia takut ada penonton masuk membawa durian.
Kemudian, dia bicara lintas benua. Dari Singapura ke Hongkong, ke Jepang, ke Afrika, ke Amerika, ke Jerman, lalu kombinasi antara India dan Skotlandia.
“Menu” utama yang paling dia tonjolkan adalah saat masuk sesi Jerman, berlanjut ke India dan Skotlandia di akhir.
Salah satu bahasa yang dia pelajari adalah Jerman. Alasannya dulu sangat manusiawi, supaya dia bisa berbincang lebih akrab dengan ayahnya yang asal Swiss dan berbahasa Jerman.
Dia lalu menyebutkan ada satu kata dalam bahasa Jerman yang tidak diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Yaitu “schadenfreude” (baca: shadenfroide).
Karena dalam masa perang Jerman punya image jahat, kata ini awalnya memang terkesan kejam. “Schaden” artinya kesialan atau petaka, sedangkan “freude” artinya kebahagiaan. Dijadikan satu, artinya kurang lebih “menemukan kesenangan/kebahagiaan dalam kesusahan atau kesengsaraan orang lain.”
Ketika diucapkan dalam lafal Jerman yang tegas, memang ada kesan ini kata yang kejam. Bahkan sadis. Tapi lantas Noah mengingatkan bahwa kita semua pada dasarnya “mengidap” schadenfreude.
Dia memberi contoh saat kita naik mobil. Jalur kita lancar mulus, sementara jalur sebelah macet total. Saat kita tersenyum melihat sengsaranya pengendara di sebelah, maka kita otomatis sudah merasakan schadenfreude.
Beberapa guyonannya setelah itu, yang lintas berbagai budaya dan bahasa, selalu berkaitan dengan pengalaman schadenfreude.
Dan schadenfreude ini ada tingkatan-tingkatannya. Yang sekadar senyum lihat macet, sampai yang memang sadis dan jahat.
Sepulang dari acara itu, istilah schadenfreude terus terngiang di kepala saya. Seperti baru saja ikut kuliah, lalu ada satu pelajaran yang terus membuat kita terkesan dan penasaran.
Saya pun terus menggugel dan baca-baca soal schadenfreude ini. Dan memang topiknya banyak dibahas dalam materi-materi psikologi.
Secara umum, mengalami atau merasakan schadenfreude itu normal. Masalahnya, kalau sampai bablas, maka itu bisa menjadi indikasi gangguan kejiwaan.
Sekilas, saya sempat tergelitik. Bersama teman, saya berdiskusi dan saling mengukur. Siapa yang level schadenfreude-nya paling parah. Begitu ada ucapan “mengkapokkan” orang lain, kami langsung menyebut: “Awas schadenfreude bablas.”
Lalu, kami pun memikirkan, apakah secara umum masyarakat kita ini parah schadenfreude-nya.
Suporter sepak bola misalnya. Kalau bahagia saat tim lawan kalah, itu pasti schadenfreude. Mungkin level sangat normal. Kalau kemudian senang melihat pemain atau suporter lawan celaka, itu bisa masuk area schadenfreude yang “lampu kuning” atau lebih parah lagi.
Apalagi, schadenfreude ini bisa dipicu oleh kecemburuan sosial. Oleh perasaan ketidakadilan.
Ambil contoh, ada seorang pejabat yang ditahan karena terbukti korupsi. Ketika merasa puas melihat ini, mungkin masih masuk dalam schadenfreude normal.
Tapi, kalau ada artis/selebriti/orang kaya mengalami musibah alami. Kemudian tanpa alasan khusus merasa senang melihatnya. Maka itu bisa masuk kategori schadenfreude yang tidak sehat. Karena dasarnya murni hanya tidak suka melihat orang lain sukses.
Contoh-contoh spesifiknya sangat banyak, dan kita mungkin tiap hari merasakan berbagai level schadenfreude ini.
Saya sendiri sekarang jadi lebih peka terhadap schadenfreude. Baik terhadap yang saya rasakan/lakukan sendiri maupun yang diucapkan atau dirasakan orang lain.
Karena lebih peka, saya tentu berharap ini bisa membuat saya menjadi orang yang lebih baik. Dan kalau itu benar-benar terwujud, maka benar-benar tidak rugi saya bela-belain ke Singapura hanya untuk nonton Trevor Noah. Karena pikiran saya telah mendapatkan “asupan intelektual” baru, seperti yang sudah lama saya butuhkan… (azrul ananda)