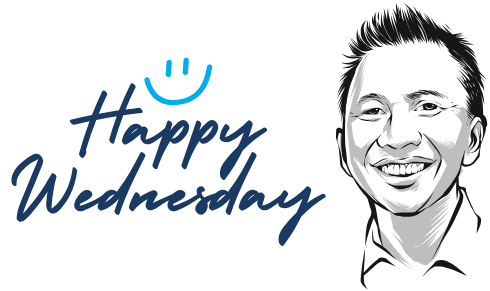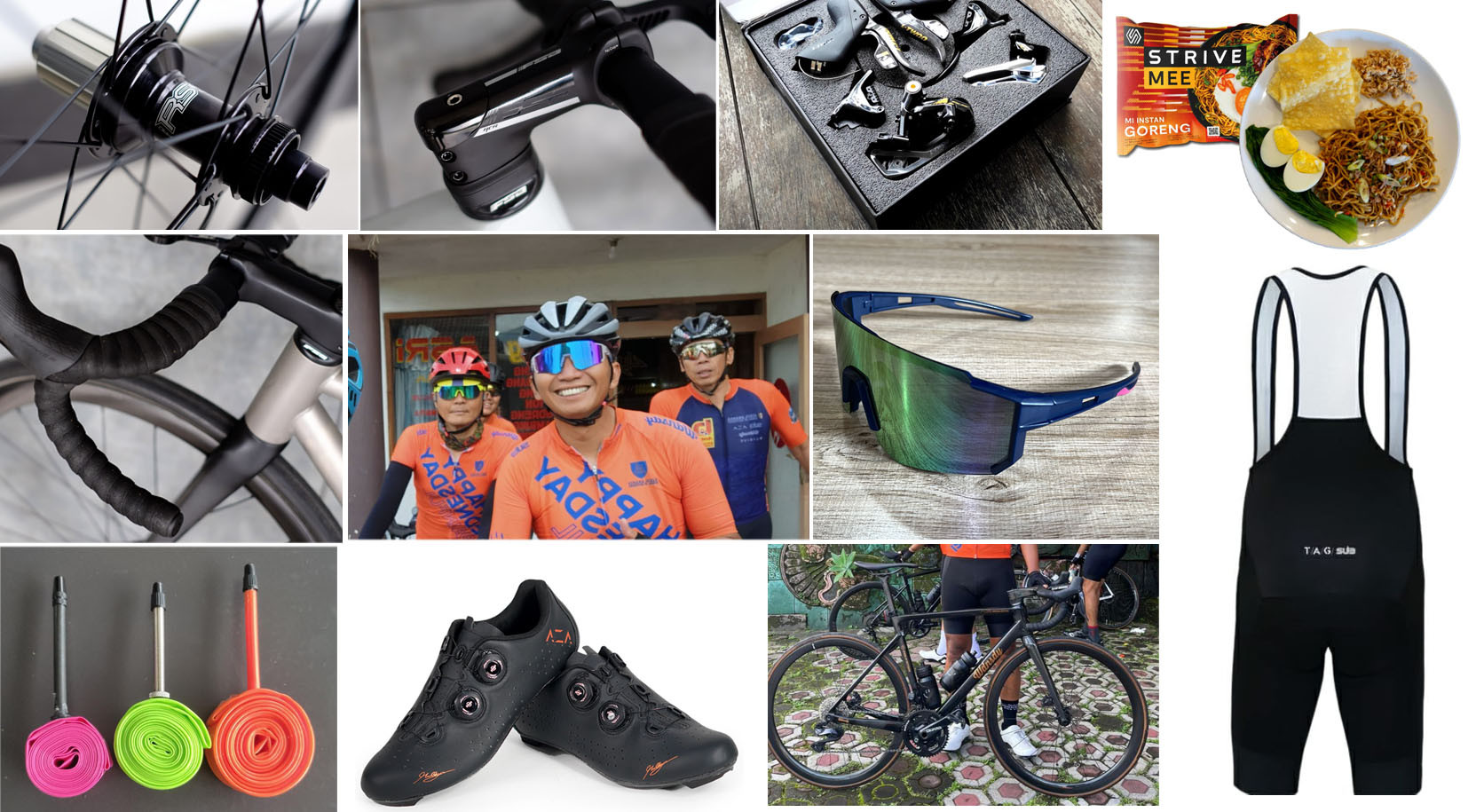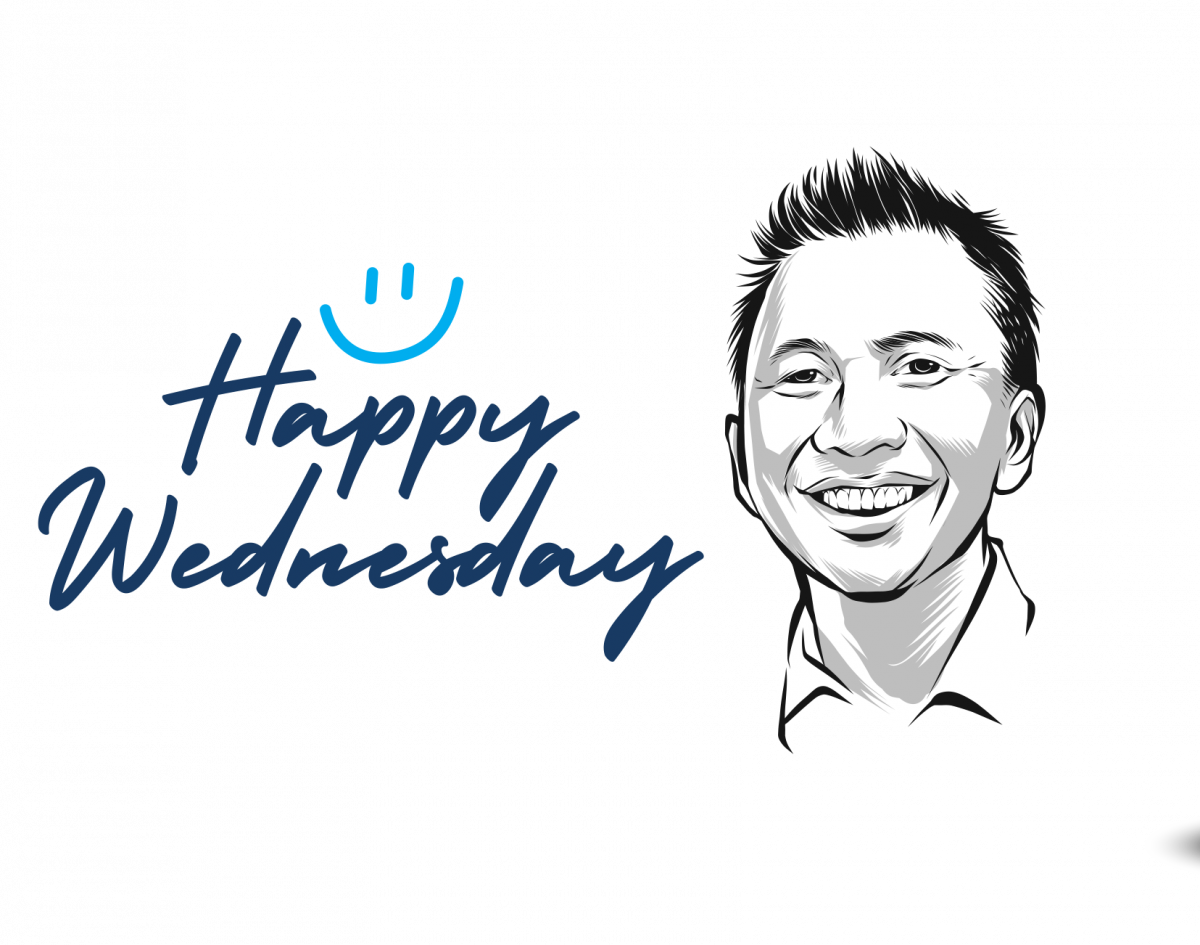Abah saya penggemar berat, bahkan mungkin tergolong penganut, Pramoedya Ananta Toer. Waktu saya masih SD, saya sudah dicekoki buku-bukunya. Padahal waktu itu masih ilegal peredarannya di Indonesia.
Saya sendiri tidak merasa dicekoki. Karena saya memang kutu buku. Karya-karya pujangga lama/baru sudah jadi koleksi saya sejak belum lulus SD. Buku-buku karya Sutan Takdir Alisjahbana, Mochtar Lubis, dan lain-lain sudah saya koleksi sejak SD.
Tapi, ayah saya selalu meninggalkan buku-buku Pramoedya Ananta Toer untuk saya baca di rumah. Apalagi waktu saya mulai suka mengetik cerita (beberapa cerpen saya waktu SD pernah dimuat di majalah anak-anak seperti Ananda).
Saya lupa apa saja kata-kata ayah saya tentang Pramoedya. Hanya satu yang sangat saya ingat: “Kalau mau belajar menulis deskripsi, harus baca buku-buku Pramoedya.”
Tentu beberapa buku itu saya baca. Mungkin karena masih SD, banyak konteksnya yang saya tidak paham. Dan waktu itu saya memang jauh lebih menggemari Trio Detektif atau Lima Sekawan. Kalau penulis Indonesia, Dwianto Setyawan. Kalau komik, Hasmi dan Gundala-nya.
Saya baru membaca lagi buku-buku Pramoedya Ananta Toer saat kuliah di Sacramento. Yaitu Tetralogi Buru alias Buru Quartet. Tapi, yang saya baca versi bahasa Inggris-nya. Mulai This Earth of Mankind, Child of All Nations, Footsteps, dan House of Glass.
This Earth of Mankind, yang judul asli Indonesia-nya Bumi Manusia, merupakan bahan tugas saya untuk kelas English Writing, Critical Thinking.
Mungkin karena saya masih menuju usia 20 tahun, kesukaan saya waktu itu terfokus pada kisah cinta Minke dan Annelies. Walau sebenarnya buku itu memiliki banyak layer (lapisan) cerita. Mungkin karena waktu itu banyak energi saya juga untuk cari pacar dan pacaran!
Saya selalu bersyukur, saya ini orang beruntung. Baru beberapa tahun setelah pulang ke Indonesia, saya bertemu dengan Pramoedya Ananta Toer. Beliau sedang ke Surabaya dan mengunjungi kantor saya. Kami makan siang santai. Kalau tidak salah hanya berempat. Pramoedya dan pendampingnya, saya, plus pakar budaya/rekan kerja Arief Santosa.
Saya tidak akan menyombongkan diri, bahwa saya kenal baik dengan beliau. Saya hanya bertemu sekali itu saja. Percakapan juga banyak tidak serius. Selain kegiatan waktu itu di Surabaya, juga sedikit soal kesehatan. Terus terang, saya termasuk jauh dari rokok, dan beliau terus merokok. Saat saya tanya apakah tidak apa-apa, beliau menunjukkan beberapa butir bawang putih.
Saya tidak ingat kata-kata pastinya. Yang jelas, butiran-butiran bawang putih itu untuk mengimbangi segala hal buruk yang dia konsumsi.
Waktu itu, beliau juga menyinggung kalau ada upaya untuk mengusung karya-karyanya ke layar lebar. Maklum, waktu itu film Indonesia sedang kembali heboh, tidak lama setelah sukses spektakuler Ada Apa dengan Cinta?.
Belasan tahun kemudian, lama setelah kepergian beliau, film itu akhirnya tiba. Bumi Manusia, disutradarai Hanung Bramantyo.
Lagi-lagi saya beruntung bisa ikut menghadiri gala premiere-nya. Beruntung karena filmnya yang datang ke saya. Lokasi acara di Surabaya Town Square, tempat kantor DBL Indonesia dan 300 karyawannya berada. Di lokasi itu pula ada Wdnsdy Café, sebuah cycling café hasil kolaborasi dengan beberapa sahabat bersepeda.
Kebetulan lagi, istri saya kenal Hanung. Istri saya pernah beberapa kali bekerja dengannya saat dulu masih aktif di dunia model dan akting.
Dunia ini kecil bukan? Karena itu, jangan pernah remehkan hal-hal kecil karena segalanya bisa menyambung di kemudian hari. Seperti kata-kata kondang Steve Jobs: Connecting the Dots.
Anyway, salah satu orang pertama yang menanyai pendapat soal film itu adalah sang maniak Pramoedya Ananta Toer: Abah saya. Maklum dia sedang banyak urusan di luar negeri.
Abah juga bertanya apakah saya akan menulis soal film itu. Saya tahu kenapa dia bertanya. Dia pasti gatal ingin menulis soal Pramoedya di blog pribadinya yang fenomenal popularitasnya, Disway.id.
Saya jawab iya. Dan Anda sedang membacanya sekarang.
Jadi, bagaimana filmnya? Saya akan memposisikan diri sebagai remaja yang membaca dan meresensi Bumi Manusia sebagai tugas kuliah dulu. Dalam posisi ini, tentu saya sangat menyukainya. Sebuah drama percintaan luar biasa di awal 1900-an, antara seorang remaja pribumi Minke dan seorang gadis Indo Annelies Mellema.
Sebagai orang Surabaya saya juga suka, karena lokasinya memang di Surabaya. Dan keluarga Annelies adalah pemilik peternakan, perkebunan, dan tanah seluas 180 hektare di kawasan Wonokromo dan sekitar. Jadi, kalau kita sekarang di dunia Bumi Manusia, maka Surabaya Town Square –lokasi gala premiere-- itu mungkin berdiri di tanah milik keluarga Mellema! Begitu pula Kebun Binatang Surabaya!
Berdurasi tiga jam, film ini terlihat sangat berupaya menyampaikan sebisa mungkin isi Bumi Manusia. Khususnya di seputar kisah cinta Minke dan Annelies. Hanung menunjukkan kelasnya. He did a wonderful job mencoba menyampaikannya menjadi sebuah film yang indah.
Sebelum film dimulai, saya sempat khawatir tentang bagaimana Nyai Ontosoroh, ibu Annelies, ditampilkan. Karena menurut saya dia itu sosok kunci Bumi Manusia. Bukan Minke, bukan Annelies. Alhamdulillah, Sha Ine Febriyanti did a good job memerankan karakter kompleks itu.
Sayang, tiga jam tidaklah cukup untuk menceritakan seluruh isi dan konteks Bumi Manusia. Tiga jam itu pas-pasan untuk menceritakan cinta Minke dan Annelies. Tiga jam sendiri mungkin tidak cukup untuk menunjukkan siapa Nyai Ontosoroh yang sebenarnya. Lengkap dengan back story-nya (latar belakang) yang tragis sebagai bunga Tulangan, bunga Sidoarjo.
Belum lagi sosok-sosok lain yang masing-masing layak dapat film sendiri. Jean Marais, sahabat sekaligus rekan bisnis Minke, layak dapat film sendiri. Dia hanya muncul beberapa menit di film. Padahal, cerita hidup pria Prancis ini merupakan drama indah sendiri.
Bagaimana Marais awalnya pelukis jalanan di Paris, lalu ikutan jadi tentara Belanda, menjalani perang di Aceh, jatuh cinta dengan perempuan Aceh, kemudian kehilangan perempuan itu sekaligus salah satu kakinya.
Herman Mellema, ayah Annelies, bisa dapat film sendiri. Dia hanya muncul beberapa menit, kebanyakan dalam kondisi mabuk dan buruk. Padahal dia juga punya cerita panjang dari Belanda sampai Surabaya. Dari kebaikan hingga kehancuran pribadi.
Bahkan Maiko, sang pekerja seks komersial asal Jepang, layak dapat film sendiri! Di film ini dia hanya dapat porsi beberapa detik. Sangat satu dimensi. Yaitu “sekadar” PSK yang melayani Herman dan anaknya Robert (kakak Annelies), sekaligus orang yang meracuni Herman Mellema.
Di buku, Maiko punya cerita satu bab sendiri. Bagaimana dia masuk ke dunia gelap ini. Berpindah dari Jepang, ke Hongkong, ke Singapura, lalu ke Betawi dan akhirnya ke rumah bordil Ah Tjong di Surabaya.
Cerita Maiko ini malah bikin saya heran pada Abah saya. Berarti dulu waktu saya masih SD, saya sudah disuruh baca tentang perjalanan hidup seorang pekerja seks, sekaligus belajar tentang sistem dan cara bisnis itu beroperasi! Bahkan, di buku ditulis “kasta” pekerja seks apa saja yang paling laris di Singapura. Apakah Jepang, Tiongkok, dan kalau dari Indonesia dari wilayah mana. Wkwkwkwk…
Robert Mellema, kakak Annelies, di novel juga diceritakan lebih kompleks. Mengapa dia bisa begitu benci pada keluarga sendiri. Bukan sekadar kakak jahat begitu saja seperti di film. Seperti kenyataan bukan? Bahwa dalam hidup ini semua ada sebab akibatnya.
Dan, salah satu tokoh favorit saya, Darsam, juga layak dapat film sendiri. Seorang pendekar Madura yang begitu loyal menjaga Nyai Ontosoroh dan Annelies, siap mengorbankan nyawa sambil tetap mengedepankan common sense.
Ya, Bumi Manusia adalah sebuah novel yang begitu kompleks. Nanang Prianto, mantan wakil pemimpin redaksi harian ternama yang kini bekerja bersama saya, bilang kalau Bumi Manusia seharusnya tidak jadi film. Seharusnya jadi serial yang begitu mengikat seperti Game of Thrones.
Terus terang, setelah melihat film itu, saya kembali mengambil buku This Earth of Mankind di rak ruang hobi saya. Buku itu tidaklah tebal, versi bahasa Inggris ini “hanya” 360-an halaman. Buku segitu bisa dengan mudah saya lahap dalam sehari. Maksimal dua hari.
Saya kemudian ke Gramedia dan beli lagi versi Indonesia-nya. Memang lebih tebal, 500-an halaman. Tapi itu pun beberapa hari bisa tamat. Lebih tebal karena ukuran font-nya lebih besar. Serta bahasa Indonesia menurut saya tidak sepresisi bahasa Inggris, sehingga butuh kalimat/paragraf lebih panjang untuk menyampaikan hal yang sama.
Setelah membaca lagi, saya jadi semakin kagum. Betapa luar biasanya seorang Pramoedya. Dan sekarang, lebih dari 20 tahun sejak kali terakhir membacanya, saya jadi melihat buku itu dengan konteks lebih luas. Bukan sekadar drama percintaan, drama kemanusiaan, kebangkitan/perjuangan perempuan, maupun pelajaran sejarah. Buku ini juga layak jadi bahan diskusi di kelas-kelas bisnis!
Bagaimana Minke bekerja menjual furniture, bagaimana dia meladeni konsumen perempuan yang cerewet. Juga bagaimana dia menyikapi idealisme Jean Marais, seniman yang merancang dan membuat barang-barang dagangan itu. Menyeimbangkan antara selera konsumen yang belum tentu bagus dengan idealisme Jean Marais yang belum tentu “menjual.”
Lalu bagaimana Herman Mellema dengan tekun menularkan ilmu kepada Nyai Ontosoroh, termasuk cara menjalankan bisnis dalam skala besar. Ini juga menjadi bukti, kita tidak harus sekolah untuk menimba ilmu. Nyai Ontosoroh (nama asli Sanikem) tidak pernah sekolah, tapi punya kemampuan dan kemauan keras untuk terus belajar.
“Hidup dapat memberikan segala pada barang siapa tahu dan pandai menerima,” kata Nyai Ontosoroh.
Ya, ada begitu banyak kutipan super di Bumi Manusia (buku). Termasuk yang bertema motivasi bisnis/manajemen. Salah satu yang digunakan di film: “Berbahagialah dia yang makan dari keringatnya sendiri, bersuka karena usahanya sendiri, dan maju karena pengalamannya sendiri.” Ini pujian Nyai Ontosoroh kepada Minke yang bekerja sambil sekolah.
Yang lain? “Memerintah pekerja pun kau tak bisa, karena kau tak bisa memerintah dirimu sendiri. Memerintah diri sendiri kau tak bisa, karena kau tak mau bekerja.”
Atau dari Herman Mellema saat mengajari Nyai Ontosoroh untuk selalu rapi dalam berdandan dan menjalani hidup: “Kau harus selalu kelihatan cantik, Nyai. Muka yang kusut dan pakaian berantakan juga pencerminan perusahaan yang kusut-berantakan, tak dapat dipercaya.”
Bukan hanya omongan, Nyai Ontosoroh juga menjadi contoh apa itu kerja keras. Dia sama sekali tak pernah libur. Dia mengizinkan karyawannya yang ratusan untuk mengambil libur, tapi dia sendiri tidak libur. Dan dia mengajari Annelies untuk juga terus bekerja tanpa libur.
Luar biasa memang. Satu buku bisa mengandung begitu banyak angle yang bisa dieksplorasi.
Dan ini masih satu buku. Masih ada tiga lagi sambungannya! Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca.
Bumi Manusia ini hanyalah sebuah permulaan. Kalau dari awal “dijual” sebagai drama percintaan, dan orang suka hanya karena sebagai drama percintaan, takutnya mereka akan kecewa pada sekuel-sekuelnya…
Spoiler warning: Di awal buku kedua (Anak Semua Bangsa), kita sudah tidak perlu lagi membahas banyak soal Annelies… (azrul ananda)